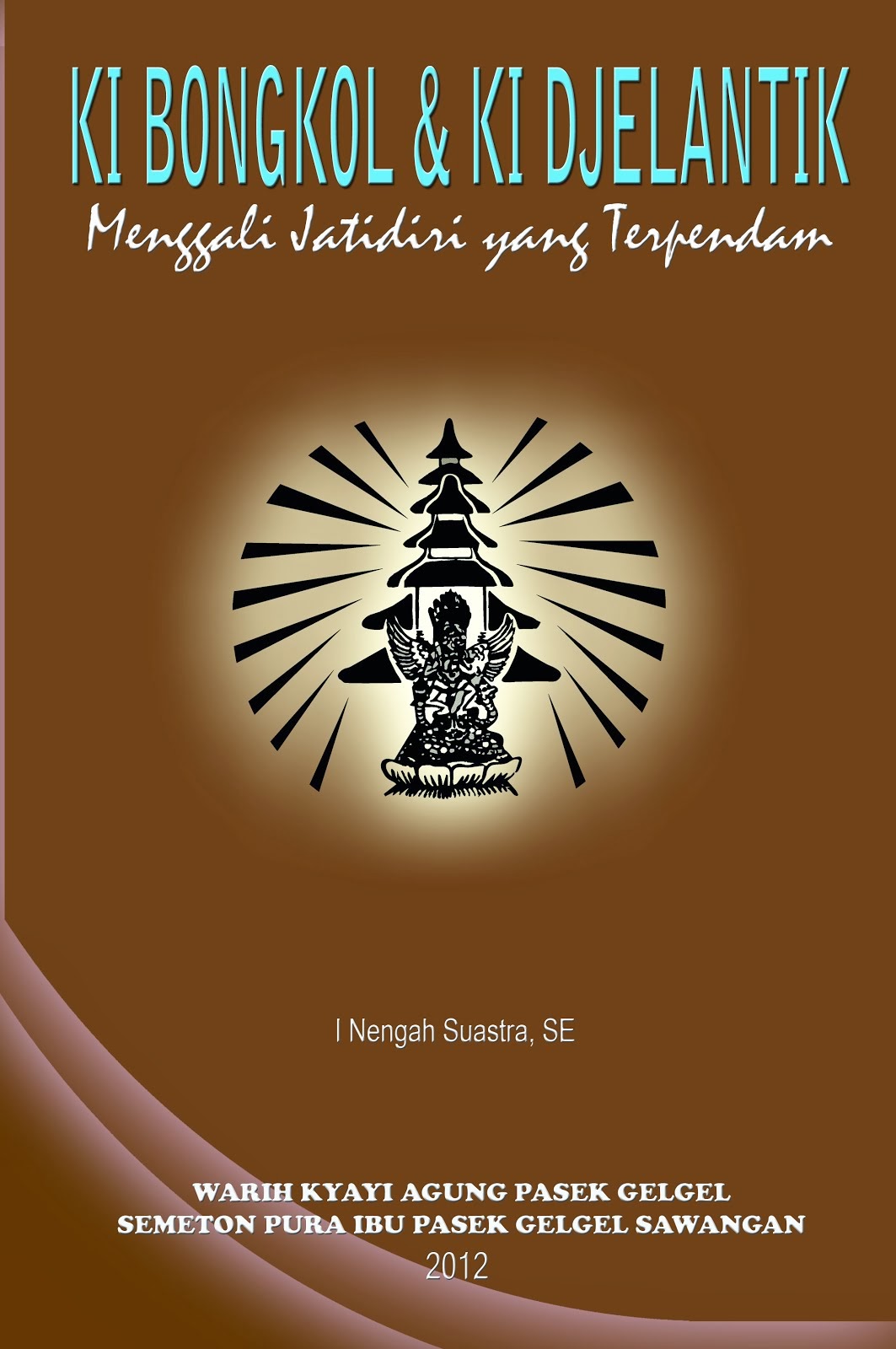Banten Sebagai Penguatan Konsep Hidup
BANTEN merupakan visualisasi dari ajaran tattwa dan susila Hindu yang memiliki tujuan mengarahkan, menuntun manusia guna tumbuhnya sifat-sifat yang mulia dalam diri. Oleh sebab itu apa yang ada dibalik banten itu ternyata sangat kaya akan konsep hidup yang bersifat universal, yang wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari misalnya: Banten Peras, Banten ini lambang perjuangan hidup dan doa untuk mencapai kesuksesan (Prasiddha) dalam kehidupan ini. Sebagai manusia normal kesuksesan dalam hidup merupakan dambaan setiap orang. Lalu apa yang harus dilakukan dalam meraih sukses tersebut. Dalam Banten Pras kesuksesan itu digambarkan dengan jelas sekali dinyatakan : " Pras Ngaranika Prasiddha Tri Guna Sakti ", artinya Pras namanya adalah sukses (Prasiddha) dengan kuatnya Tri Guna. Tri Guna itu adalah Sattwam, Rajas dan Tamas. Apabila ketiga Guna ini berada pada struktur dan komposisi yang idial, maka ia akan menjadi kekuatan luar biasa untuk mengantarkan seseorang menuju pada kesuksesan hidup. Struktur dan komposisi idial yang dimaksud adalah apabila guna Sattwam menguasai guna Rajas dan guna Tamas. Dalam Banten Pras ketiga guna ini disimbulkan dengan benang, uang dan beras. Benang sebagai lambang Sattwam, Uang sebagai lambang Rajas, dan Beras sebagai lambang Tamas. Banten Penyeneng melambangkan konsep hidup yang berkeseimbangan, dinamis dan produktif. Hidup yang seimbang mengandung suatu arti bahwa tujuan hidup ini harus diselaraskan antara kebutuhan jasmani (material) dengan kebutuhan rokhani, dinamis mengandung arti bahwa dalam hidup ini manusia diwajibkan untuk tidak henti-hentinya mengejar kemajuan dan produktif artinya senantiasa berkarya atau mencipta yang patut diciptakan, memelihara yang patut di pelihara dan meniadakan sesuatu yang patut ditiadakan. Visualisasi dari konsep hidup yang tiga ini diwujudkan dengan bentuk sampian yang beruang tiga. Dalam usaha membangun konsep hidup ini maka manusia hendaknya memiliki pandangan yang benar. Benar dalam arti dilandasi oleh kesucian bathin. Kesucian bathin akan muncul manakala telah lenyapnya sifat-sifat negatif dalam diri. Dengan demikian barulah benih kesucian dapat disemaikan. Hal ini divisualisasikan dalam bentuk sarana yang disebut segawu tepung tawar dan beras. Banten Tulung adalah suatu banten dengan tiga kojong yang berisi nasi dan lauk pauk dan rerasmen. Makna dari banten tulung ini adalah bahwa hidup ini saling memiliki ketergantungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Ini menggambarkan manusia disamping sebagai makhluk individu juga berdimensi sebagai makhluk social. Ciri makhluk sosial adalah memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan semua komponen yang hidup di muka bumi ini. Banten Sesayut adalah suatu banten yang melambangkan perjuangan hidup manusia untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup yang disebut ayu. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini tidak dapat diwujudkan sekaligus, melainkan diraih dengan cara bertahap sesuai bentuk alas dari sesayut itu yang berbentuk bulat maiseh. Oleh karena itu dalam wujud apa kesejahteraan dan kebahagiaan itu dimohonkan disesuaikan jenis sesayut atau tebasan yang ada. Itu sebabnya banyak ditemui jenis sesayut yang masing-masing mempunyai pengharapan yang mengkhusus.Banten Dapetan adalah suatu banten yang memiliki makna untuk mencari, pengembangan kebajikan sehingga apa yang kita warisi baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang merupakan proses karma kita dimasa lampau maupun karma dimasa kini. Untuk napet (mewarisi) yang baik manusia wajib pengembangan, serta menyemai kebajikan itu kepada semua orang dengan selalu berpegang kepada Satya. Jika hal ini senantiasa dilembagakan niscaya akan dipetik hasil atau buah yang baik. Hal ini divisualisasikan dengan beras (bija) yang dicampur bunga kamboja atau cempaka (sesarik) sebagai lambang benih yang harus disemaikan, serta benang sebagai lambang kebenaran. Hal ini harus dikembangkan kesegala penjuru yang dilambangkan oleh alas sesarik yang berdimensi ke delapan penjuru mata angin. Dan masih banyak banten-banten lain yang merupakan pengejewantahan dari kebenaran ajaran Weda. **