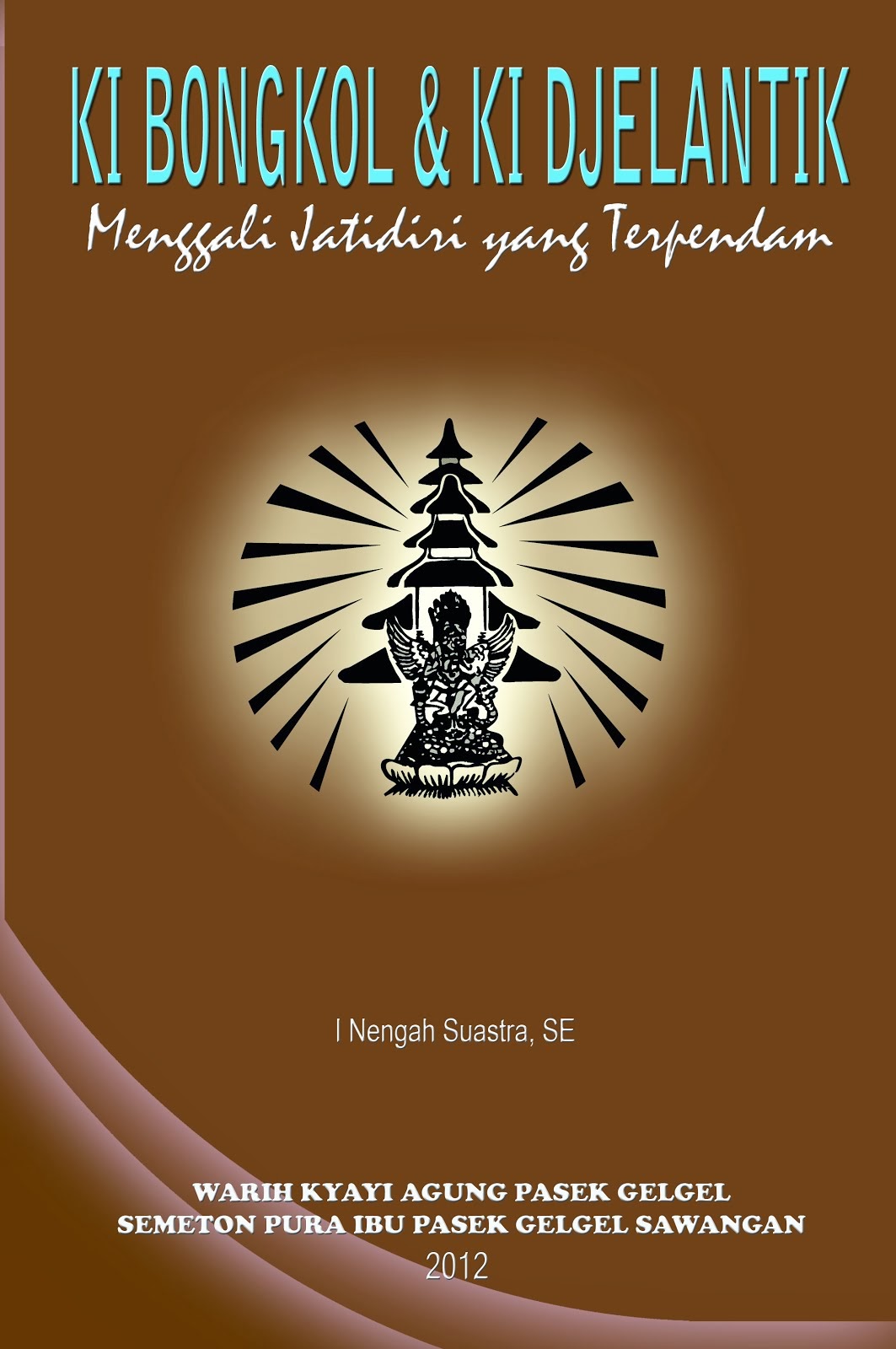SEKILAS GUNUNG BATUR DAN PURA ULUN DANU BATUR
Pada Purnama Kedasa. Sebagaimana biasa saat itu berlangsung upacara besar di Pura Ulun Danu Batur. Desa Batur, Kintamani, Bangli. Pura Ulun Danur Batur sebagai kahyangan jagat umat Hindu di Bali, dimulialan sebagai stana Bhatara Wisnu. Sedangkan Bhatara Siwa di Besakih dan Brahma di Lempuyang Luhur, Karangasem.
SEBAGAI stana Bhatara Wisnu, yang dalam konsep masyarakat Batur terkenal dengan sebutan Bhatari Dewi Danuh, Pura Ulun Danu memiliki historis yang sangat menarik, baik berkembang secara turun-temurun sebagai cerita rakyat yang hidup di Batur serta masyarakat pemuja di sekitarnya, maupun sebagaimana termuat dalam beberapa babad.
Paling tidak, sejarah Pura Ulun Danu Batur termuat dalam Babad Pasek yang ditulis oleh Jro Mangku Gede Ketut Soebandi, Babad Pasek yang ditulis oleh I Gusti Bagus Sugriwa, serta Babad Kayu Selem yang disalin oleh Drs. Putu Budiastra, dkk. Bahkan sejarah pura ini juga termuat dalam Raja Purana Pura Ulun Danu Batur I dan II yang disusun oleh Drs. I Putu Budiastra, dkk. Sejarah dan terjadinya Gunung Batur serta Pura Ulun Danu Batur dapat diuraikan sebagai berikut.
Zaman Bahari
Dalam versi Babad Pasek dan Babad Kayu Selem, semula Pulau Bali dan Selaparang masih menyatu dan terombang-ambing dihanyutkan arus samudera. Waktu itu, Ida Bhatara Hyang Pasupati yang berstana di Puncak Gunung Prabulingga (Gunung Semeru) merasa kasihan melihat kedua pulau tersebut terombang-ambing. Beliau lantas mengutus tiga putranya yakni Bhatara Hyang Geni Jaya, Bhatara Hyang Mahadewa, dan Bhatari Dewi Danu agar menyusup ke Pulau Bali.
''Nanda bertiga, Geni Jaya, Putra Jaya (Mahadewa) dan Dwi Danuh hendaknya nanda bertiga datang ke Pulau Bali agar pulau tersebut tidak terombang-ambing, '' demikian sabda Hyang Pasupati. ''Mohon maaf, nanda ayahanda, nanda masih sangat muda dan belum berpengalaman, '' jawab ketiga putranya. ''Nanda jangan khawatir,'' tandas Hyang Pasupati. Begitulah, akhirnya Hyang Pasupati memasukkan ketiga putranya ke dalam kelapa gading, dan dihanyutkan lewat dasar laut. Secara gaib ketiganya tiba di Gunung Agung, dan Beliau sepakat mencari tempat bersemayam. Bhatara Hyang Geni Jaya memutuskan berstana di Gunung Lempuyang, Bhatara Putra Jaya (Mahadewa) berstana di Gunung Agung dengan Pura Besakih, dan Bhatari Dewi Danu memilih sebuah kubangan besar yakni Danau Batur dengan Gunung Batur sebagai puncaknya.
Setelah itu, Hyang Pasupati mengirim empat putra lainnya, seterusnya berstana di Andakasa, Gunung Beratan (Pucak Mangu), Gunung Batukaru, dan Pejeng. Sehingga bila dirunut secara historis, khususnya dari kajian babad, seharusnya di Bali ada sapta kahyangan bukannya sad kahyangan.
Purana Tatwa Batur
Siapa dan bagaimana Gunung Batur serta Beliau yang bersemayam di Pura Ulun Danu Batur, tersirat pula dalam salah satu bagian: Raja Purana Pura Ulun Danu Batur -- Purana Tatwa. Begitu pula, uraian ini sangat populer di sekitar pemuja Pura Ulun Danu Batur.
Kisahnya adalah: Tersebutlah tiga putra Bhatara Indra yang berstana di Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar, bertanya pada kakeknya Hyang Pasupati di Gunung Semeru. ''Mohon maaf Kakek Bhatara, siapakah gerangan ayahanda cucunda?''
''Oh kalau itu cucunda tanyakan, biar nanti bibi yang mengantar cucunda menjumpai ayahanda''. ''Nah nanda I Ratu Ayu Mas Membah (sebutan Bhatari Dewi Danu), sekarang berangkatlah ke Tirta Empul antarkan kemenakan nanda menghadap ayahandanya. ''
Demikianlah I Ratu Ayu Mas Membah berangkat ke Bali diiringi ketiga putra Bhatara Indra serta I Ratu Ayu Arak Api. Tak terkisahkan di jalan ketiganya telah tiba di stana Bhatara Indra di Tirta Empul, dan langsung menghadap Bhatara Indra. ''Oh dinda Dewi datang, siapa kiranya anak tampak ketiga ini?''.
''Oh kanda tidak kenal, inilah ketiga putra kanda yang yang semula di Semeru bersama ayahanda''. ''Oh begitu, kemarilah Nanda bertiga maaf ayahanda sudah tua, dan pandangan ayah sudah berkurang''.
''Nah, nanda yang tertua, ayah tak punya apa-apa, kiranya apa yang akan nanda minta?''. ''Mohon maaf ayahanda dan kiranya ada nanda memohon goa yang besar serta air suci''. ''Oh kalau itu, baiklah, kini ayah beri nama nanda I Ratu Gede Gunung Agung, dan di sanalah nanda menetap di bekas tempat ayah di pertengahan Gunung Agung, dan ini air suci, nanti beri nama tirta Mas Manik Kusuma.'' Begitulah, beliau lantas berstana di sekitar pertengahan Gunung Agung. Selanjutnya, ''Nanda yang kedua I Gede Nengah, apa yang nanda minta?''. ''Hamba juga minta air suci''. ''Nah nanda I Gede Nengah tempatkanlah air suci ini di barat laut tempat ibunda, dan beri nama tirta Mas Manik Mampeh. Letaknya di barat laut Danau Batur.''
''Nah nanda yang terkecil namun badannya terbesar apa yang nanda minta?''. ''Nanda minta balai agung''. Beliau diberikan dan distanakan di Manukaya. Lalu, Bhatara Indra meminta Mangku Pucangan agar mengantarkan I Ratu Ayu Mas Membah menuju tempatnya. Beliau dijunjung menuju arah timur laut, di suatu tempat. Karena kepayahan menjunjung I Ratu Ayu Mas Membah istirahat sambil nafasnya ''ah-ah, ah'', sehingga tempat itu disebut Basang Ah.
Perjalanan dilanjutkan dan tiba di Desa Pengotan. Saat itu penduduk sedang rapat. Mangku Pucangan berkata: ''Tuan berhenti sebentar bersidang, ini Paduka datang''.
Mereka tertawa karena melihat wujud Ida Bhatari layaknya ukiran janur yang dijunjung oleh Mangku Pucangan. ''Oh ha, ha, ha dimana ada Bhatari, orang menjunjung sampyan (ukiran rontal) banyak capak''. Ida Bhatari berkenan menunjukkan wajah aslinya dan berkata, ''Nanti jika kalian semua memuja kepada-Ku, masih di pintu gerbang akan diterbangkan angin''. Begitulah yang terjadi sampai saat ini, biasanya sesaji warga Pengotan, hancur di candi Pura Ulun Danu Batur.
Perjalanan dilanjutkan. Sampai di Penelokan Mangku Pucangan melihat air payau sangat luas dan Bhatari Ratu Ayu Mas Membah meminta mencari benang dan bulu ayam. Benda tersebut dilemparkan ke tengah payau lalu benang tersebut diikuti oleh Mangku Pucangan. Tepat di tengah air payau Beliau berkata, ''Sudahlah Mangku Pucangan tempatkan Aku di sini''.
Begitu Beliau diturunkan, mendadak tempat ini makin tinggi terus menjadi sebuah gunung tepat di tengah payau (danau). Gunung itu diberi nama Gunung Tempur/ Tempuh Hyang. Artinya bekas pijakan kaki Ida Bhatari, sehingga menjadi Gunung Tampur Hyang. Nama lain dari Gunung Tampur Hyang adalah Gunung Lebah yang artinya sebuah gunung yang letaknya di dataran rendah, serta Gunung Sinarata -- yang diartikan oleh masyarakat Batur ''gunung yang mendapat sinar matahari secara merata''.
Demikianlah ceritanya, dan secara berkelanjutan akibat letusan Gunung Batur, mereka berpindah ke atas, serta puranya bernama Pura Ulun Danu Batur yang pujawalinya jatuh setiap Purnama Kedasa.
* Jro Mangku I Ketut Riana